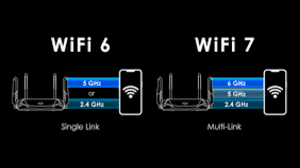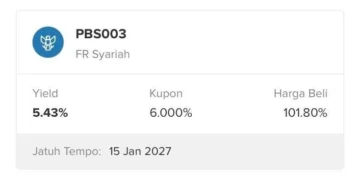Bangga Indonesia, Banyuwangi – Beberapa waktu lalu, pernyataan presiden terkait keinginan agar diberi kritik yang membangun kepada pemerintah sehingga pelayanan publik lebih optimal lagi cukup membuat heboh. Presiden bahkan menekankan bahwa kritik atau masukan kepada pelayanan publik wajib dilakukan untuk mendorong standar kualitas pelayanan. Berjarak sekitar sepekan, Jokowi meminta DPR merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bila dinilai tidak bisa memberikan keadilan. Ia bahkan mengatakan akan meminta DPR menghapus pasal-pasal karet yang ada di UU ITE karena pasal-pasal itu menjadi hulu dari persoalan hukum UU tersebut.
Sudah dua belas tahun UU ITE diterapkan. Banyak masyarakat terjerat dalam aturan ini. Tahun 2013, pelaporan kasus UU ITE meningkat empat kali lipat, dan sepanjang 2019, upaya kriminalisasi lewat pasal-pasal karet UU ITE 2019 makin merajalela. Anton Muhajir dari SAFEnet berkata setidaknya ada sekitar 3.100 kasus. sepanjang 2019 ada pola lebih luas dan lebar bagi korban-korban pasal karet UU ITE. Pada tahun-tahun sebelumnya lebih banyak menyasar ke jurnalis dan aktivis, tetapi pada 2019 rentan menyasar ke akademisi dan dosen.
Melihat jatuh korban yang jumlahnya sudah mencapai ribuan, bahkan menyasar semua kalangan, banyak pihak mempertanyakan permintaan Presiden yang mendadak minta dikritik dan merevisi UU ITE. Apakah maksud dibalik itu. Bukannya selama ini justru telah banyak kritik yang ditujukan pada kebijakan-kebijakan pemerintah, yang nyatanya justru pemberi kritik berakhir di bui.
Kepentingan Dibalik Wacana Revisi UU ITE
Dilansir dari Kompas.com (20/2/2021), Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai ada kesamaan antara situasi Indonesia saat ini dibandingkan dengan situasi era Orde Baru. Busyro pun menilai situasi saat ini sudah bergerak ke arah neo otoritarianisme. Ia mengatakan ada tiga indikator pemerintahan Jokowi sudah mengarah ke neo otoritarianisme.
Pertama, masifnya buzzer atau pendengung di media sosial. Yang banyak terjadi ketika orang mengkritik langsung diberi label macam-macam. Seperti intoleran, anti-Pancasila, anti-NKRI, radikal, dan sejenisnya. Kalau tidak, mereka yang kritis diserang secara verbal baik individunya ataupun profesinya. Kedua, adanya teror-teror dengan meretas alat komunikasi, termasuk teror kepada aktivis kampus. Ia mencontohkan kasus teror kepada civitas Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang hendak menggelar diskusi terkait pemakzulan presiden. Ketiga, terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilainya seolah-olah melegalkan perbuatan para buzzer. Menurut Busyro, UU ITE memiliki karakter seperti pelembagaan buzzer yang sudah memakan banyak korban.
Oleh karena itu, tentu saja yang paling diuntungkan dengan kehadiran UU ITE ini adalah pemerintah, pengusaha, dan pejabat negara. UU ITE itu ibarat sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Sekali terjerat UU ITE, kritik dapat dibungkam, suara oposisi berkurang, dan kebijakan pun melenggang tanpa hambatan. Kritik terhadap pemerintah kerap ditafsiri sebagai ujaran kebencian, penghinaan, atau pencemaran nama baik. Ruang kritik makin sempit tatkala UU ITE menjadi senjata andalan membungkam lawan politik.
Revisi UU ITE bisa juga menjadi cara penguasa melindungi para pendukungnya. Mengingat tak jarang pula buzzer penguasa kerap dilaporkan menggunakan UU ini tetapi hampir tidak ada yang diproses. Jika UU ini benar-benar direvisi, para pendukung penguasa dengan bebas bernapas lega dan bebas dari jerat hukum. Namun, beda urusan bila hal itu berkaitan dengan rakyat kritis.
Hipokrisi Demokrasi, Antikritik
Ternyata, memang inilah resiko ketika umat mengambil sistem demokrasi kapitalis neoliberal yang cenderung prokepentingan kapitalis. Karena pada praktiknya, sistem seperti ini sudah pasti akan menabrak proses partisipasi rakyat, sekaligus menihilkan proses dialog yang akomodatif terhadap kepentingan dan maslahat rakyat banyak. Gagalnya demokrasi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, ketidakadilan yang tampak nyata, perilaku tamak dan bejat pejabat yang kian merajalela dan berbagai fakta-fakta buruk penerapan demokrasi inilah yang terus menuai kekecewaan masyarakat. Wajar jika sepanjang sistem ini diterapkan, negeri ini tak pernah sepi dari protes dan keriuhan. Kalaulah tak terjun di aksi massa, rakyat tanpa tabu mengungkap keluh kesahnya di ruang-ruang publik sebebas media sosial. Itulah kenapa, jagat maya begitu ramai membincang realitas hidup yang makin sulit. Membincang para penguasa yang semena-mena, juga asing yang kian merajalela.
Hingga di satu titik, tentulah kondisi ini akan dianggap membahayakan rezim. Karena bagaimana pun, penguasa tetap membutuhkan legitimasi alias dukungan dari rakyat mereka, meski legitimasi itu harus diperoleh dengan cara paksa. Dan sebagai pemegang kendali atas sumber-sumber kekuatan, negara akan dengan mudah melakukan semuanya. Media mainstream, kekuatan militer, polisi, bahkan ormas, semua digerakkan untuk membangun dukungan. Dan di saat sama, digunakan untuk memberangus kebebasan berpendapat dan kebebasan berorganisasi di tengah masyarakat yang berpotensi melakukan penolakan. Maka strategi belah bambu pun menjadi cara yang efektif untuk meredam suara-suara sumbang. Buzzer politik sekaligus agen-agen intelijen pun menjadi bisnis menjanjikan. Mereka direkrut untuk mengukuhkan agenda setting yang sudah ditetapkan. Maka, keadaan pun menjadi aman terkendali. Meski sewaktu-waktu siap memanas dan meledak tak terkendali.
Dalam sistem kapitalisme sekuler, definisi politik adalah kekuasaan untuk kepentingan para kapitalis, bukan kemaslahatan rakyat. Sementara demokrasi melegalisasi kebijakan seolah atas nama rakyat, padahal untuk kepentingan kapitalis. Karena itu, setiap kritik yang membela kepentingan rakyat dianggap ancaman kepentingan kapitalis dan merongrong kekuasaan rezim.
Untuk itu, berbagai cara mulai dari stigma hingga represif dilakukan demi memperkukuh hegemoni penjajahan kapitalisme dan mencegah kebangkitan Islam sebagai solusi atas negara ini. Sungguh nyata bahwa kebebasan ala demokrasi hanyalah hipokrit dan tumbuhnya budaya kritik jelas hanya ilusi semata.
Sinyal Lonceng Kematian Demokrasi
Sayangnya masih banyak yang tidak sadar, sistem demokrasi benar-benar sudah tidak layak dijadikan sebagai sistem pemerintahan utamanya di negeri-negeri kaum muslimin. Padahal, pakar-pakar sistem pemerintahan mereka justru memprediksi kehancuran sistem ini. Munculnya buku How Democracies Die yang ditulis oleh akademisi dan ilmuan politik dari Harvard University semakin menguak cacat sistem demokrasi dan prediksi kuat menuju jurang kematian.
Empat indikator kehancuran demokrasi yang disebutkan dalam buku tersebut semua mengarah pada represif dan otoriternya penguasa dalam membungkam nalar publik diantaranya membatasi hak politik rakyat, mengkriminaliasasi lawan politik, hingga kesiagaan dengan kekuatan militer dalam membungkam sipil. Dan faktanya ini semua akan semakin berjalan mulus dengan diterapkannya RUU ITE.
Fakta lain menunjukkan gagalnya demokrasi adalah Laporan “Democracy Index 2020: in Sickness and in Health?” atau Laporan Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan secara global di tahun 2020 demokrasi mengalami pukulan besar. Hampir 70% negara mencatat penurunan dengan skor rata-rata global turun dari 5,44 (dalam skala 0-10) menjadi 5,37. Merupakan level terendah sejak indeks dimulai pada tahun 2006.
Indeks ini memberikan gambaran singkat tentang keadaan demokrasi dunia untuk 165 negara merdeka dan dua teritorial, mendasarkan pada lima kategori yaitu proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, berfungsinya pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik.
Jika demikian, bukankah ini adalah sinyal kuat bagi kejatuhan demokrasi. Dan bahkan para penganutnya justru telah nyata meragukan masa depannya bagi kemaslahatan dunia.
Khilafah, Alternatif Sistem
Sudah saatnya umat ini sadar. Sudah saatnya pula mereka memahami tipuan narasi sistem demokrasi kapitalis liberal. Banyak yang mengira, dengan demokrasi mereka akan bebas menentukan sikap, bebas berperilaku dan berpendapat, tidak terkungkung oleh aturan. Sungguh pikiran yang tidak tepat. Bagaimana bisa hidup tanpa aturan, sedangkan berkendara di jalan raya saja butuh aturan. Apalagi sebuah kehidupan yang kompleks, tentu sangat butuh.
Dunia sudah terlalu lama diatur dalam sistem demokrasi kapitalis hasil akal pikir manusia yang justru mengantarkan kesengsaraan bagi umat. Kaum muslimin dan umat manusia semuanya butuh sebuah tatanan global yang sahih, yang datang dari pencipta mereka- Allah SWT. Oleh karena itu, hanya sistem khilafahlah sebagai sebuah tatanan global yang bersumber dari wahyu Allah, mampu mengantarkan manusia hidup mulia dan sejahtera. Khilafah mampu pula mengantarkan keadilan. Dengan mendudukkan kedaulatan di tangan syara’, maka akan lahir hukum yang tak berpihak. Rakyat maupun penguasa mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sama-sama terikat dengan syariat Allah.
Sistem Khilafah juga sangat terbuka dengan kritik dan aduan dari rakyatnya. Siapa pun bebas memberikan kritik dan aduan yang disebut muhasabah lil hukkam, yaitu aktivitas mengoreksi penguasa yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Dengan kritik dan pengaduan rakyatlah, penguasa akan terselamatkan dari sikap zalim dan mungkar. Sebab, penguasa di sistem Khilafah menyadari besarnya pertanggungjawaban mereka kelak di akhirat. Masihkah kita meragukan sistem aturan yang mulia ini, yang telah menghantarkan umat islam selama 14 abad pada kejayaan yang tertinggi. Wallahu a’lam bisshowab
FATA VIDARI, S.Pd ( Praktisi pendidikan, Banyuwangi, Jawa Timur )